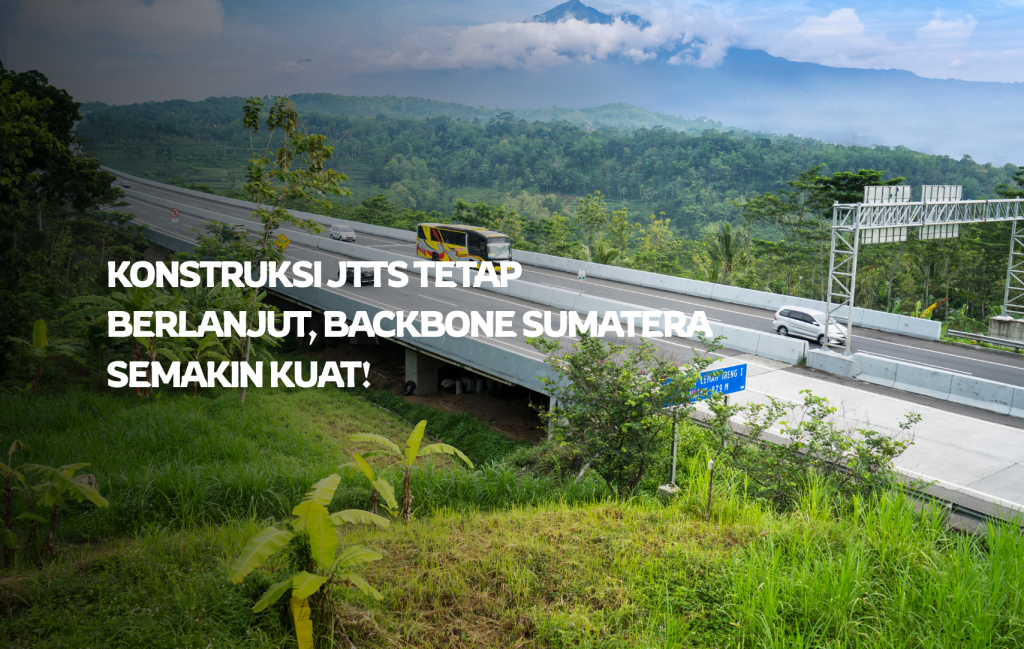MEMPERJUANGKAN KELAPA SAWIT DALAM PERANG DAGANG

Kiprah kelapa sawit sebagai salah satu komoditas penting bagi Sumatra kembali menghadapi tantangan. Genderang perang dagang yang ditabuh oleh Presiden Donald Trump kepada dunia telah meningkatkan ketidakpastian global termasuk potensi devisa ekspor kelapa sawit yang berpotensi mengalami ganjalan. Tapi, melihat posisi saat ini, seharusnya Indonesia tidak perlu terlalu khawatir.
Sebagai kompetitor utama, negeri tirai bambu yang kini membuka tirainya untuk menjadi raksasa baru sebagai pesaing Amerika Serikat dikenakan tarif yang cukup tinggi sebesar 34 persen. Sejumlah negara mitra lainnya terkena level tarif most-favored nations/MFN (tarif generik bagi anggota WTO) yang bervariasi mulai 10 persen hingga 40 persen, termasuk Indonesia yang terkena 32 persen. Tentunya sebagai negara yang sepadan, Tiongkok tidak tinggal diam. Retaliasi dilancarkan dengan menerapkan tarif balasan yang lebih tinggi terhadap produk impor dari Amerika Serikat sebesar 84 persen.
Kebijakan Amerika Serikat ini tak mungkin dilawan dengan tangan kosong. Langkah negosiasi sepertinya akan menjadi opsi paling feasible dengan upaya mendapatkan keringanan tarif secara bilateral. Produk industri manufaktur menjadi sektor yang paling rentan. Akan tetapi terdapat produk industri pengolahan komoditas yang masih menjadi primadona bagi Indonesia untuk mendulang devisa, seperti kelapa sawit. Hingga saat ini pangsa produk kelapa sawit dari Indonesia masih dapat menancapkan posisi lebih dari 50 persen pasokan dunia.
Kelapa Sawit Sebagai Sumber Devisa Sumatera
Wilayah Sumatera dan Kalimantan telah berkontribusi besar dalam sumbangan devisa dari kelapa sawit bagi Indonesia. Setidaknya, lebih dari 60 persen devisa kelapa sawit Sumatera berasal dari ekspor crude palm oil (CPO), yang merupakan hasil olahan tandan buah kelapa sawit segar (TBS). Dari CPO, olahan minyak nabati baik untuk keperluan energi (melalui biofuel), ketahanan pangan (melalui minyak goreng), hingga industri oleokimia (seperti sabun dan kosmetik) lebih unggul dibanding hasil ekstraksi minyak nabati dari tanaman lainnya, seperti bunga matahari, kedelai, jagung, hingga rapeseed. Positioning yang semakin baik telah menggerek harga CPO internasional semakin tinggi.
Perdagangan CPO ke Amerika Serikat dari Sumatera berada pada peringkat ke empat terbesar, di bawah India, Uni Eropa, Tiongkok, bahkan Pakistan. Preferensi masyarakat Amerika Serikat yang sedikit berbeda menjadikan ketergantungan Amerika Serikat kepada CPO tidak setinggi India maupun Tiongkok. Bahkan banyak yang menganggap dampak penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat tersebut minimal.
Lolosnya Indonesia dari tuduhan penyebab deforestasi oleh Uni Eropa membuka menjaga asa meraup untung. Pemanfaatan energi hijau terbarukan dari biofuel kini menjadi tren baru di tengah gencarnya perkembangan mobil listrik. Pasar-pasar potensial lainnya seperti Timur Tengah dan Afrika masih sangat terbuka lebar.
Tantangannya kini berbalik ke Sumatra. Seberapa siap kelapa sawit ini dikembangkan lebih lanjut. Sebagai komoditas primer, kelapa sawit memiliki banyak potensi nilai tambah yang bisa dihasilkan. Biofuel, minyak goreng, hingga turunan oleokimia menjadi contoh lazim di antaranya. Nilai tambah yang dihasilkan bisa mencapai 300 persen dari harganya sebagai barang primer. Daya beli masyarakat juga dapat ditingkatkan bila dapat melakukannya.
Kebutuhan kelapa sawit juga tinggi di dalam negeri. Di tengah upaya Pemerintah mendorong kemandirian energi melalui B40 dan kemandirian pangan melalui kebijakan domestic market obligations (DMO), kebutuhan kelapa sawit kian tinggi. Pengusaha kian menghadapi dilema karena cuan dari ekspor lebih tinggi daripada memasok pasar dalam negeri di tengah harga sawit yang tenang bertengger di atas $1000 per metrik ton, sementara harga jual domestik masih berada di bawah level ekuivalen $700 per metrik ton. Selain DMO, ekspor CPO juga dikenakan pajak sebesar 7,5% dari harga referensi.
Dilema Taktik Memenangkan Sawit
Semangat deregulasi yang dilontarkan Pemerintah untuk mengefisiensikan industri kelapa sawit dalam bersaing di pasar global antara lain melalui dorongan produktivitas dan diplomasi internasional. Meski demikian, kemandirian ekonomi yang terus digaungkan pemerintah menempatkan kelapa sawit sebagai komoditas yang strategis. Dilema dapat terjadi apabila tidak ada kejelasan antara prioritas kemandirian pangan dan energi dengan prioritas daya saing ekspor.
Strategi jalan tengah yang dapat diambil adalah bagaimana mewujudkan keberlangsungan industri hilir kelapa sawit nasional dalam rangka penciptaan nilai tambah. Kebutuhan biofuel pascapenerapan kebijakan B40 diprediksi akan mendorong pengembangan industri hilir CPO lebih luas. Perluasan kapasitas terpasang industri pengolahan biodiesel dapat didorong, seperti yang saat ini dilakukan di beberapa kawasan industri seperti KEK Sei Mangkei di Sumatera Utara.
Tidak hanya itu, pengembangan produk oleokimia dapat memberikan alternatif penciptaan daya saing kelapa sawit lebih tinggi. Sebagai contoh, pengembangan produk surfaktan dan kosmetik yang berasal dari kelapa sawit dapat meningkatkan nilai tambah industri hingga 300% dengan permintaan domestik maupun ekspor yang masih tinggi. Selain itu, produk oleokimia juga dapat menjadi substitusi dari petrokimia karena lebih ramah lingkungan dan berbasis nabati.
Kebijakan Komisi Uni Eropa melalui renewable energy directive (RED II) yang menargetkan 32 persen kebutuhan energi dipasok dari sumber terbarukan, diestimasi akan meningkatkan compound annnual growth rate (CAGR) pasar biodiesel hingga 5 persen sampai dengan 2033. Situasi ini tentu memberikan secercah harapan di tengah situasi global yang tidak menentu, dan pasokan minyak nabati alternatif global yang masih terbatas pasokannya. Lolosnya Indonesia pada sengketa sawit di WTO semakin memperkokoh pengakuan dunia terhadap jenis minyak nabati ini.